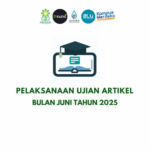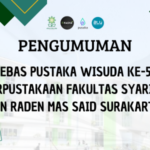Oleh: Ahmad Muhamad Mustain Nasoha
Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden Republik Indonesia ke 7 Ir. H. Joko Widodo telah menjadi isu yang menyita perhatian luas di tengah masyarakat. Perdebatan ini tidak hanya bergema dalam ruang publik, tetapi juga memasuki ranah akademis dan diskursus hukum, memunculkan pertanyaan serius tentang integritas kepemimpinan nasional. Dalam konteks ini, penting untuk mengedepankan analisis yang bersifat objektif dan berbasis hukum guna menjernihkan polemik yang berpotensi menimbulkan kegaduhan politik serta ketidakpercayaan terhadap institusi negara.
Tulisan ini bertujuan untuk memberikan tinjauan komprehensif terhadap permasalahan tersebut, dengan pendekatan normatif, yurisprudensial, dan perbandingan konstitusional. Fokus kajian mencakup aspek yuridis-formil terkait keabsahan dokumen akademik, prinsip etika dalam penyelenggaraan negara, serta legitimasi konstitusional seorang kepala negara. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya menegaskan bahwa isu keaslian ijazah bukan sekadar persoalan administratif, melainkan juga menyangkut penghormatan terhadap supremasi hukum, asas praduga tak bersalah, serta integritas sistem demokrasi konstitusional di Indonesia.
Isu mengenai validitas ijazah Presiden Republik Indonesia ke 7 Ir. H. Joko Widodo, khususnya dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Surakarta, pertama kali mencuat ke ruang publik melalui berbagai saluran informasi non-resmi. Meskipun tuduhan pemalsuan tersebut telah berkali-kali dibantah oleh institusi kredibel seperti UGM, Kementerian Pendidikan, serta dibahas dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilu, narasi ini terus direproduksi di media sosial dan ruang politik. Dalam situasi semacam ini, diperlukan suatu tinjauan hukum yang tidak hanya bersandar pada fakta formil, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan ketertiban publik dalam kerangka negara hukum.
Izinkan saya dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki, mengkaji dan memberikan argumentasi dari berbagai perspektif:
1. Tinjauan Yuridis atas Keabsahan Ijazah
Dalam sistem hukum positif Indonesia, keabsahan dokumen akademik—termasuk ijazah—diakui sebagai bagian dari legal acts (perbuatan hukum) yang sah apabila dikeluarkan oleh institusi yang memiliki otoritas formal. Berdasarkan lex generalis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, secara eksplisit Pasal 69 dan 70 menyebutkan bahwa ijazah merupakan dokumen resmi negara (documento publico), yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi dan memiliki legal standing dalam sistem pendidikan nasional.
Lebih jauh, dalam perspektif hukum pidana, Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa pemalsuan surat (falsificatio documenti) merupakan tindak pidana apabila dilakukan dengan niat untuk menipu (dolus) dan memperoleh keuntungan secara melawan hukum (contra legem). Oleh karena itu, setiap tuduhan pemalsuan ijazah harus dibuktikan melalui proses hukum yang sah, disertai dengan alat bukti yang memenuhi asas verba volant, scripta manent—kata-kata bisa hilang, tetapi bukti tertulis tetap.
Dalam konteks polemik ijazah Presiden Republik Indonesia ke 7 Ir. H. Joko Widodo, tidak ditemukan adanya acte juridique berupa laporan pidana yang berdasar dan didukung oleh bukti autentik yang menyatakan bahwa dokumen ijazah tersebut merupakan hasil pemalsuan. Lebih dari itu, tidak pernah ada satu pun putusan pengadilan yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia ke 7 Ir. H. Joko Widodo. Bahkan, gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait keaslian ijazah tersebut telah ditolak secara formal dan materil oleh majelis hakim. Penolakan ini menegaskan prinsip res judicata pro veritate habetur—putusan pengadilan dianggap sebagai kebenaran hukum yang mengikat.
Dalam sistem hukum Belanda yang menjadi salah satu sumber reception hukum nasional Indonesia, pemalsuan dokumen publik termasuk ijazah diatur dalam Wetboek van Strafrecht (KUHP Belanda), khususnya Pasal 225. Sama seperti di Indonesia, pemalsuan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila dapat dibuktikan adanya maksud penipuan (bedoeling tot misleiding). Pengadilan tidak akan menjatuhkan sanksi pidana tanpa adanya pembuktian unsur subjektif dan objektif secara utuh, sesuai asas nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege—tidak ada kejahatan tanpa undang-undang, tidak ada hukuman tanpa dasar hukum.
Sementara itu, dalam sistem hukum Prancis, Code Pénal mengatur bahwa dokumen resmi, termasuk diplôme, hanya dapat dipersoalkan keabsahannya melalui pembuktian forensik yang ketat dan dilakukan oleh lembaga negara yang berwenang. Tidak diakuinya tuduhan berbasis persepsi atau narasi tanpa alat bukti, selaras dengan prinsip la preuve incombe à celui qui affirme—beban pembuktian ada pada pihak yang menuduh.
Dengan demikian, dalam perspektif hukum perbandingan, konstruksi yuridis dalam sistem hukum Indonesia terkait keabsahan ijazah Presiden Republik Indonesia ke 7 Ir. H. Joko Widodo sejalan dengan sistem hukum negara-negara civil law lain. Tanpa adanya legal finding yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum, tuduhan terhadap keaslian ijazah tidak dapat dianggap sah secara hukum.
Secara yuridis-formil, sampai hari ini tidak terdapat dasar hukum yang valid untuk menyatakan ijazah Presiden Republik Indonesia ke 7 Ir. H. Joko Widodo sebagai dokumen palsu. Dalam rule of law state (Rechtsstaat), setiap tuduhan harus diuji dalam koridor hukum, bukan berdasarkan opini atau asumsi politis semata. Oleh karena itu, polemik ini hendaknya disikapi dengan kehati-hatian dan penghormatan terhadap mekanisme hukum yang berlaku, demi menjaga integritas konstitusional dan stabilitas demokrasi.
2. Asas Etika Publik dan Moralitas Kepemimpinan
Sebagai public office holder, seorang Presiden tidak hanya terikat oleh norma-norma hukum positif, melainkan juga oleh prinsip-prinsip public ethics dan moral integrity, yang menjadi fondasi kepercayaan publik (public trust doctrine). Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang menekankan pentingnya asas akuntabilitas, transparansi, dan kejujuran dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.
Salah satu pilar etika publik adalah veracitas atau kejujuran, termasuk dalam menyampaikan identitas dan riwayat pendidikan. Namun, dalam kasus Presiden Republik Indonesia ke 7 Ir. H. Joko Widodo, tidak ditemukan adanya false statement atau deklarasi publik yang bertentangan dengan fakta hukum. Bahkan, Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai issuing authority secara resmi telah mengonfirmasi status Joko Widodo sebagai alumnus Fakultas Kehutanan angkatan 1980. Pernyataan ini diperkuat oleh dokumentasi internal kampus serta kesaksian dosen dan teman seangkatan.
Dalam asas hukum, dikenal adagium “in dubio pro reo”—dalam keraguan, berpihaklah pada terdakwa. Maka selama tidak terdapat bukti hukum yang sahih dan final menunjukkan bahwa Presiden menyampaikan informasi palsu, asas integritas tetap dianggap intact dan presumption of regularity tetap berlaku. Dengan demikian, setiap narasi yang menuduh kebohongan publik tanpa dasar hukum dapat dianggap sebagai bentuk trial by media, yang bertentangan dengan asas due process of law dan keadilan substantif.
3. Aspek Konstitusional: Legitimasi Jabatan Presiden
Konstitusi Negara Republik Indonesia mengatur secara tegas dalam Pasal 6 Ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden harus memiliki pendidikan minimal setingkat Sekolah Menengah Atas. Ketentuan tersebut kemudian diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menetapkan bahwa salah satu syarat administratif pencalonan presiden adalah melampirkan dokumen ijazah pendidikan formal.
Dalam dua kali proses pemilihan umum (2014 dan 2019), Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi telah melakukan verifikasi dokumen dan menyatakan bahwa semua persyaratan administratif yang diajukan oleh calon atas nama Joko Widodo adalah lengkap, sah, dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak terdapat keberatan hukum yang dibuktikan dan diakui melalui keputusan penyelenggara pemilu maupun pengadilan pemilu.
Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of the constitution dalam putusan-putusan perkara sengketa hasil Pemilu Presiden, tidak pernah menemukan indikasi pelanggaran administratif berupa pemalsuan ijazah atau dokumen persyaratan lainnya. Maka, berdasarkan prinsip “lex superior derogat legi inferiori”, ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu yang dijalankan sesuai prosedur hukum tidak dapat diganggu gugat oleh narasi tanpa dasar yuridis.
Dengan demikian, secara konstitusional, jabatan Presiden Jokowi memiliki legal legitimacy dan democratic validity yang sah. Adagium “fiat justicia ruat caelum”—keadilan harus ditegakkan walau langit runtuh—mengingatkan kita bahwa keadilan harus ditegakkan berdasarkan bukti dan hukum, bukan oleh prasangka atau tekanan politik.
4. Polemik Sebagai Serangan Politik: Analisis Hukum Kritik Publik
Dalam negara hukum yang demokratis (rechtsstaat), kebebasan berekspresi merupakan hak asasi fundamental yang dijamin secara konstitusional. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menjamin setiap orang untuk menyatakan pendapat secara bebas, baik lisan maupun tulisan. Kebebasan ini menjadi prasyarat utama dalam memastikan public accountability pejabat negara, termasuk Presiden.
Namun, sebagaimana ditegaskan oleh adagium hukum “abusus non tollit usum” (penyalahgunaan tidak membatalkan penggunaan), kebebasan berekspresi tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk menyampaikan tuduhan tanpa dasar hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, kritik yang tidak berdasar dan dilakukan dengan malice atau niat jahat dapat dikualifikasikan sebagai defamation atau false accusation, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik. Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang melarang penyebaran berita bohong yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.
Dengan demikian, apabila tuduhan terkait ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke 7 Ir. H. Joko Widodo dilakukan tanpa evidentiary basis dan tidak melalui jalur hukum formal, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar hukum pidana. Dalam kerangka comparative legal studies, negara-negara dengan sistem hukum yang sejalan dengan Indonesia, seperti Malaysia dan Filipina, juga mengatur batas antara free speech dan defamatory content dalam kerangka perlindungan terhadap dignity of public officials.
Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam menyampaikan kritik terhadap pejabat negara, agar tidak bergeser dari constitutional discourse ke arah character assassination yang menggerus kualitas demokrasi itu sendiri.
5. Penutup
Sebagai akademisi dan sarjana hukum, penulis menghormati hak setiap warga negara untuk mengemukakan pendapat, termasuk keraguan terhadap keaslian dokumen publik pejabat negara. Dalam negara demokratis yang menjunjung tinggi asas keterbukaan (open government), kritik adalah bagian dari dinamika sehat dalam kontrol publik terhadap kekuasaan.
Namun demikian, dalam sistem hukum modern yang berlandaskan pada asas due process of law dan rule of law, setiap tuduhan harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang sah dan konstitusional. Keraguan—betapa pun kerasnya—tidak dapat berdiri sebagai kebenaran tanpa bukti yang diuji di hadapan forum resmi, yakni pengadilan. Hal ini sejalan dengan asas universal dalam hukum pembuktian: “Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat”, yakni “Beban pembuktian terletak pada pihak yang menuduh, bukan pada pihak yang menyangkal.”
Dengan demikian, pembuktian keabsahan ijazah Presiden Republik Indonesia ke 7 Ir. H. Joko Widodo bukanlah kewajiban dari pihak yang dituduh untuk meyakinkan publik, melainkan menjadi beban hukum dari pihak yang mengajukan tuduhan untuk membuktikan secara objektif dan dapat diverifikasi melalui proses peradilan. Tanpa adanya judicial verdict yang sah, maka tuduhan tersebut tetap berada dalam wilayah spekulatif dan tidak dapat dijadikan dasar untuk mendelegitimasi posisi hukum Presiden dalam kerangka konstitusi.