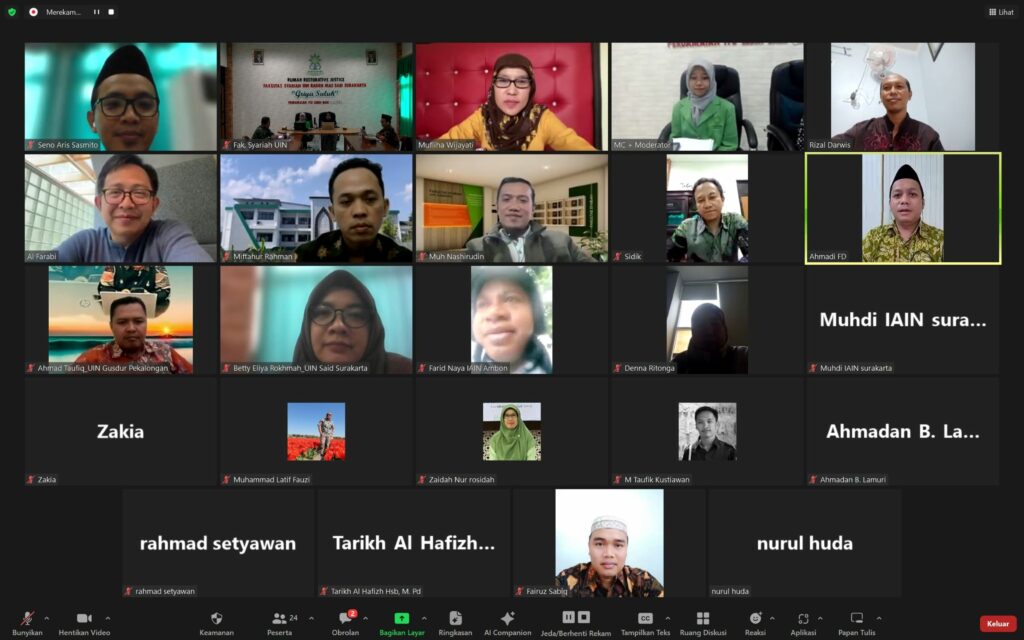FASYA-Konsorsium Ilmu Syariah (KISAH) Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta mengadakan Webinar Nasional Bedah Disertasi berjudul ‘Matrilineal Islam: State Islamic Law and Everyday Practices of Marriage and Divorce among People of Mukomuko-Bengkulu, Sumatra, Indonesia’ pada Kamis, (21/03/2024).
Hadir sebagai narasumber utama Al Farabi, M.H.I., Ph.D., penulis disertasi sekaligus dosen program studi (prodi) Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Bertindak sebagai pembahas disertasi adalah Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I., Guru Besar bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung. Bertindak sebagai moderator pada kegiatan ini Roykhatun Nikmah, M.H., dosen prodi HKI Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
Titik Temu Hukum Negara dan Hukum Adat di Masyarakat
Pada Rabu, (21/08/2021), Al Farabi pernah mendiskusikan tema Otonomi Peradilan Islam di Indonesia yang menjadi ruh utama disertasinya. (Ulasan selengkapnya ada di link ini.) Pada kesempatan ini beliau menjelaskan proses terjal mengapa otonomi peradilan diperlukan di Indonesia.
Riset disertasi berjudul ‘Matrilineal Islam: State Islamic Law and Everyday Practices of Marriage and Divorce among People of Mukomuko-Bengkulu, Sumatra, Indonesia’ bermaksud mengeksplorasi kajian sosio-legal di antara hukum negara dan realita sosial hukum adat yang mengandung gesekan, dilema, dan kerumitannya yang khas.
Skema legislasi hukum yang cenderung top-down dianggap kurang solutif bagi permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Maka, mengetengahkan realita sosial hukum adat menunjukkan ada opsi bottom-up di bidang peradilan yang solutif bagi kebuntuan di antara elemen hukum yang ada.
Everyday practices pada masyarakat Mukomuko di Bengkulu menunjukkan keunikan karakter masyarakatnya yang menganut matrilineal (sistem kekerabatan dari pihak ibu). Ketika terjadi konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian, sistem pembagian harta bersama (gono-gini) mengatur bahwa pihak istri mendapatkan bagian 50%, sementara suami hanya 25%, dan sisanya 25% diberikan kepada pihak anak.
Dalam suatu kasus, pihak suami mengajukan keberatan kepada pengadilan atas besaran pembagian harta gono-gini tersebut dan berhasil mendapatkan hak 50% atas aset keluarga yang dimiliki bersama. Namun, dalam prakteknya di masyarakat Mukomuko, ada beberapa aset harta yang tidak dapat dieksekusi atas alasan hukum adat dan menimbulkan masalah baru, yakni penolakan sekaligus pemaksaan kehendak dari kedua kubu suami dan istri (dan anak yang berpihak pada kubu istri).
Menurut Al Farabi, cara hakim melihat kasus di atas dan menyelesaikannya dapat dilakukan dengan menggunakan perspektif otonomi peradilan (autonomy of court). Misalnya, dengan menentukan kasus tersebut sebagai broken marriage dan selanjutnya berimplikasi pada putusan hukum yang berposisi netral. Putusan ini dilakukan agar memungkinkan tercapainya keadilan bagi kedua belah pihak. Melalui perspektif otonomi peradilan, hakim ‘perlu’ memihak korban sehingga putusan akhir peradilan menjadi adil bagi semua pihak.
Fakta sosial di Mukomuko dan sebagian masyarakat Indonesia yang masih kukuh menerapkan hukum adat tentu membutuhkan perspektif otonomi peradilan. Hal ini sejalan dengan gagasan Prof. Adriaan Bedner tentang ‘legal differentiation’ (pembedaan hukum) demi tercapainya keadilan hukum bagi masyarakat Indonesia.
Sejalan dengan Prof. Bedner yang merupakan pembimbing disertasi Al Farabi, ruang-ruang akademik di kampus perlu membahas lebih mendalam dan terbuka tentang gesekan antar hukum yang terjadi di Indonesia. Struktur kurikulum pada mata kuliah hukum perkawinan, misalnya, perlu membahas poin-poin dalam perundang-undangan yang berpotensi memunculkan multitafsir di kalangan praktisi peradilan. Dengan begitu, baik dosen maupun mahasiswa terbiasa memperbincangkan realita penerapan hukum di Indonesia secara lebih komprehensif.
Mengapresiasi Praktik Kehidupan Masyarakat Lokal
Prof. Mufliha Wijayati memulai diskusi dengan mengapresiasi kejelian Al Farabi melihat realita sosial di kawasan periferi untuk disajikan sebagai fakta dan perbincangan hukum yang menarik, yang kelak dapat memberi kontribusi bagi kekayaan perspektif peradilan hukum di Indonesia.
Sebagai pembahas disertasi, Prof. Mufliha melihat sisi unik disertasi karya Al Farabi yang perlu diulas lebih lanjut, yakni (1) apakah disertasi ini berusaha melihat sisi resiliensi hukum adat ataukah sisi marjinalisasi hukum adat oleh negara, dan (2) apakah disertasi ini berusaha melihat konstestasi atau pergumulan yang alamiah di antara hukum adat dan hukum negara.
Untuk menjawab pertanyaan di atas, Prof. Mufliha mengidentifikasi 4 temuan penting dalam penelitian Al Farabi. Pertama, pergumulan hukum Islam mazhab negara dengan tradisi masyarakat Mukomuko melahirkan kompromi dan konflik yang melibatkan banyak aktor, antara lain negara, quasi negara, dan d(ar)i luar negara (tokoh adat). Di satu sisi ada kasus yang diselesaikan di ruang pengadilan, di satu sisi penyelesaian melalui aturan adat, dan di sisi lainnya melalui perpaduan keduanya.
Kedua, perkara di Pengadilan Agama Mukomuko lebih banyak menangani persoalan penduduk migran dan urban, dan di saat yang sama masyarakat lokal jarang menggunakan instrumen pengadilan agama untuk menyelesaikan konflik di antara mereka. Berkelanjutan dengan fakta ini, pada level lokal, para hakim cenderung mengabaikan nilai-nilai tradisi lokal dan memutuskan perkara secara formalistik. Entah apa alasan di balik spirit formalistik tersebut, apakah tekanan dari negara, beban jumlah kasus yang ditangani, atau ada alasan lainnya.
Berkebalikan dengan fakta pada level lokal, pada level nasional justru menunjukkan adanya independensi hakim yang tampil ke permukaan untuk hadir dan terlibat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di tengah masyarakat.
Ketiga, sulitnya akses hukum karena semakin mahalnya biaya menyelesaikan perkara sekaligus kurangnya fasilitas sidang keliling di luar gedung pengadilan bagi masyarakat yang memiliki hambatan untuk datang ke gedung pengadilan.
Selain itu, terjadinya sentralisasi dan homogenisasi sistem peradilan yang, meskipun memberikan kepastian hukum di satu sisi, namun di saat yang lain turut serta memberangus rasa keadilan bagi tradisi lokal, serta, “…mengorbankan otonomi hakim, rasa keadilan masyarakat, dan prinsip memberikan perlindungan pada kelompok rentan (perempuan dan anak).”
Keempat, transformasi hukum keluarga Islam di tengah masyarakat melalui Pengadilan Agama tidak selalu berjalan mulus. Ada resistensi dari kalangan adat, tak terkecuali di masyarakat Mukomuko, mengingat merasa tak memerlukan keterlibatan putusan Pengadilan Agama di saat mereka dapat menyelesaikan perkara-perkara secara kekeluargaan. Berlaku sebaliknya, menang perkara di Pengadilan Agama tak selalu (do not necessarily) bisa dieksekusi secara mudah putusannya di lapangan.
Kontribusi Riset Disertasi Al Farabi tentang Matrilineal Islam
Terlepas dari tidak disinggungnya suku Semendo yang, menurut Prof. Mufliha, memiliki keserupaan karakteristik dengan masyarakat Mukomuko lantaran sama-sama menganut sistem kekerabatan matrilineal, namun hal ini tidak mengurangi lompatan kontribusi yang ditunjukkan disertasi karya Al Farabi, di mana otonomi peradilan menjadi solusi bagi tumpang tindihnya hukum di Indonesia.
Tarik ulur otonomi hakim dan unifikasi hukum negara jelas berimplikasi nyata pada kehadiran dan ketidakhadiran rasa adil yang dirasakan masyarakat sebagai warga negara. Namun, meminjam istilah agree in disagreement (sepakat dalam perbedaan) dalam kajian dialog antar agama ala Prof. Mukti Ali, otonomi peradilan yang meski tetap merepresentasikan negara dan quasi negera, perlu secara protagonis mengakomodir keragaman nilai-nilai yang telah hidup di tengah masyarakat demi terciptanya kerukunan antar warga negara. Aktor-aktor yang terlibat dalam proses peradilan perlu ‘aktif’ mencari solusi dibandingkan ‘pasif’ enggan repot mencari opsi sembari ‘menuhankan’ hukum yang hanya merepresentasikan negara an sich. Demikian. Wallaahu a’lam. (afd)